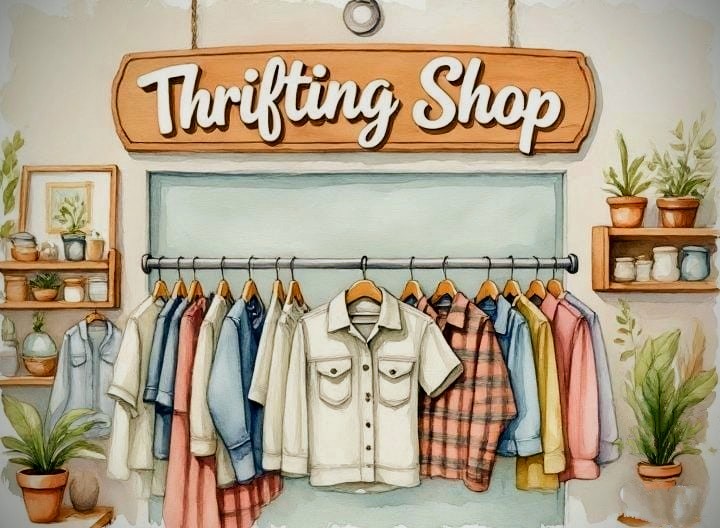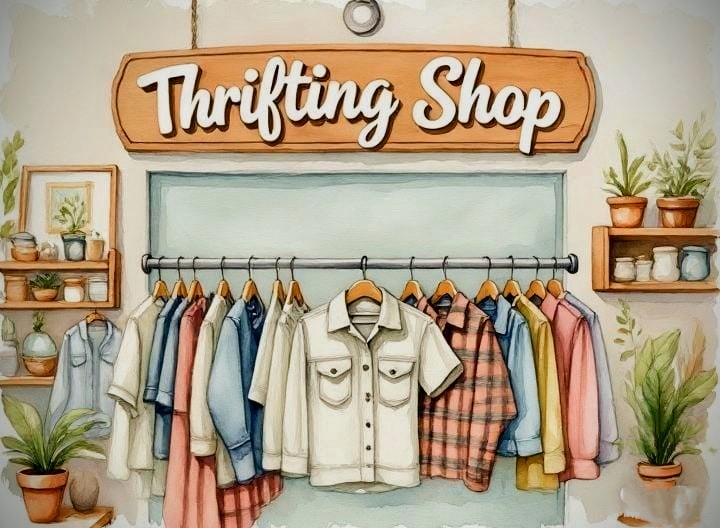
KOPIPAHIT.ID – Ada yang memabukkan dari sensasi menemukan kaos band vintage murah di lapak thrifting. Rasanya seperti menang undian yang bukan ditujukan untuk kita. Seakan-akan semesta sedang berpihak, memberi hadiah kecil di tengah hidup yang makin mahal. Tapi di balik euforia itu, ada sesuatu yang lebih gelap—lebih pahit daripada ampas kopi yang diseduh dua kali.
Sebab kalau kita mau jujur, pakaian-pakaian itu bukan sekadar “barang bekas impor”. Ia adalah jejak dosa industri konsumsi negara kaya yang dibuang jauh-jauh supaya tidak mengotori halaman mereka sendiri. Dan halaman itu, seperti biasa, adalah negara-negara berkembang—tempat di mana harga murah sering lebih penting daripada pertanyaan etis.
Sebuah riset Sustainability Journal (MDPI, 2024) menyebut dunia memperdagangkan lebih dari 24,2 miliar potong pakaian bekas tiap tahun. Industri ini bernilai US$ 4,9 miliar, atau cukup untuk membangun ulang beberapa kota kecil. Apa yang dulu dianggap sebagai pakaian yang tidak laku, rusak, out of style, atau cuma bosan dipakai dua kali di Instagram, kini menjadi komoditas global yang berpindah dari lemari orang kaya di negara maju menuju lifestyle di negara berkembang.
Laporan UNECE 2024 lebih terang-terangan lagi: perdagangan pakaian bekas naik tujuh kali lipat sejak 1990-an. Uni Eropa menyumbang 30%, China 16%, Amerika Serikat 15%. Negara maju memproduksi, memakai sebentar, foto-foto sebentar, lalu mengirimkan sisanya ke kita dengan label manis: “secondhand”. Padahal, jika kita mau bicara jujur, sebagian besar itu adalah limbah industri fashion yang gagal ditangani.
Dan limbah itu perlu tempat. Tempat yang luas, murah, dan tidak terlalu rewel. Tempat seperti Indonesia.
Tidak heran kalau impor pakaian bekas kita meroket. Dari 8 ton pada 2021, naik menjadi 26 ton pada 2022, dan—menurut laporan Mojok—melonjak brutal menjadi 3.865 ton pada 2024. Sebuah angka yang membuat kita bertanya, ini perdagangan atau pembuangan massal yang disamarkan?
Padahal industri fashion sendiri menyumbang 10% emisi karbon global (UNEP). Setiap tahun jutaan ton pakaian berakhir di landfill. Dan hanya 12% tekstil yang benar-benar didaur ulang (Ellen MacArthur Foundation). Sisanya diputar-putar dalam sirkuit global sampai ada negara yang mau menerimanya. Dan kita—dengan segala tekanan ekonomi, budaya gaya hidup, dan harga yang semakin tidak masuk akal—menjadi salah satu pasar paling subur.
Lalu lahirlah romantisasi thrifting.
Setengah penduduk Indonesia, 49,4%, mengaku pernah thrifting. Ada yang menyebutnya gaya hidup berkelanjutan. Ada yang bilang ini bentuk perlawanan terhadap fast fashion. Ada juga yang merasa lebih “estetik” atau “authentic” karena memakai baju bekas impor. Padahal kalau mau jujur, banyak dari kita thrifting karena dunia ini terlalu mahal, tapi tubuh masih butuh tertutup.
Di sisi lain, industri tekstil lokal megap-megap. Studi MDPI 2024 mencatat bahwa banjir pakaian bekas impor menggerus pasar domestik. Bagaimana tidak? Mana mungkin produsen lokal bersaing dengan harga kaos vintage luar negeri yang dijual lebih murah dari mi instan?
Begitulah paradoksnya: thrifting menyelamatkan dompet kita, tetapi mematikan ekosistem produksi kita sendiri.
Namun thrifting tetap berkembang. Ia punya estetika. Ia punya energi anak muda. Ia punya ruang ekspresi yang bebas dari kapitalisme brand besar. Tetapi di balik itu semua, ada sistem global yang bekerja halus: negara kaya membuang dosa-dosa ekologis mereka, sementara kita menyambutnya dengan kata-kata manis: “murah”, “unik”, “rare”.
Seolah-olah dunia sedang memainkan lelucon besar: mereka membuang, kita memungut; mereka menolak, kita merayakan; mereka lelah dengan konsumsi, kita kelelahan meladeni limpahannya.
Dan di antara pakaian-pakaian bekas itu—kaos band, jaket denim, hoodie universitas luar negeri—sebenarnya tersimpan pertanyaan yang lebih pahit dari semua diskon thrifting yang pernah kita dapat:
Mengapa negara kaya bisa bebas membuang limbah konsumsi mereka ke negara miskin, dan mengapa kita begitu gembira menerimanya?
Karena di atas semuanya, thrifting bukan hanya soal “hemat”. Ini adalah cermin dari ketimpangan global. Cermin yang menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi dunia hari ini, bahkan limbah pun punya arah politiknya sendiri.
Di ujung cerita, thrifting tetap bisa menjadi pilihan. Ia bisa berkelanjutan, bisa kreatif, bisa ekonomis. Tapi setidaknya, kita perlu tahu dari mana segala barang ini datang—dan mengapa ia begitu murah.
Sebab pada akhirnya, pakaian yang kita temukan itu mungkin memang menarik. Tapi sejarah di belakangnya tidak pernah benar-benar bersih.
Penulis: Heriyosh
Editor: Redaksi Kopipahit.id