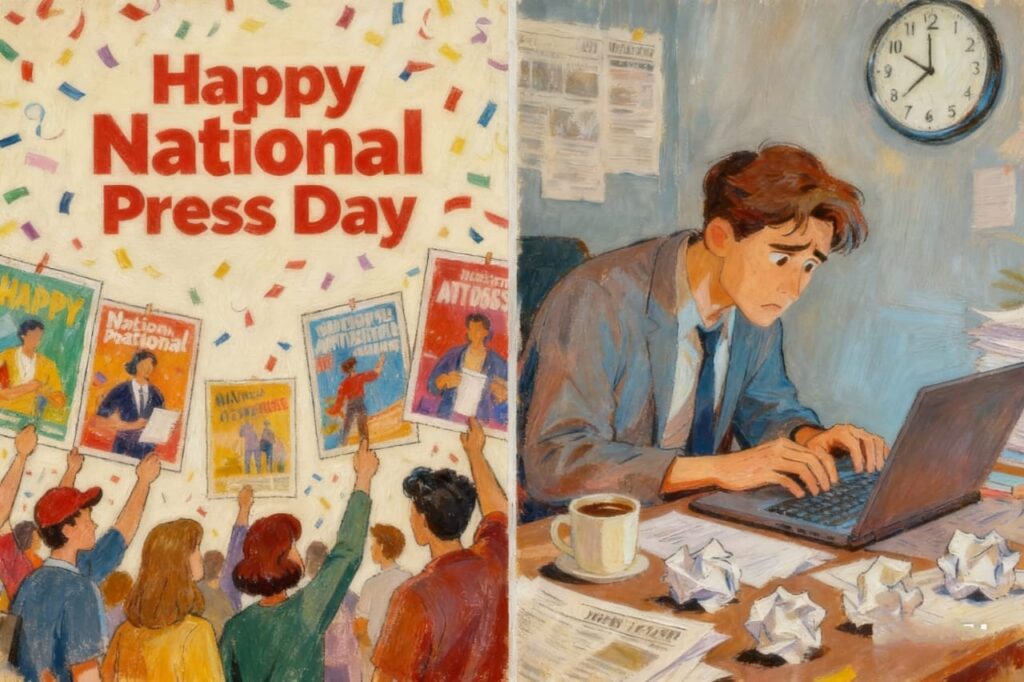KOPIPAHIT.ID – Sepasang suami istri, Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari, menggugat negara ke Mahkamah Konstitusi. Yang dipersoalkan bukan perkara ideologis besar atau konflik elite politik, melainkan sesuatu yang setiap hari kita beli, pakai, dan—tanpa sadar—kehilangan: kuota internet.
Gugatan bernomor 273/PUU-XXIII/2025 itu menyasar Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi. Intinya sederhana: mengapa sisa kuota yang telah dibayar lunas boleh dihanguskan ketika masa aktif berakhir?
Bagi Didi, pengemudi ojek online, dan Wahyu, pedagang daring, internet bukan sekadar fasilitas. Ia adalah alat produksi. Tanpa kuota, aplikasi berhenti. Tanpa aplikasi, penghasilan ikut terhenti. Dalam konteks ini, penghangusan kuota tidak lagi bersifat teknis, melainkan menyentuh hak atas kepastian hukum dan penghidupan yang layak, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H UUD 1945.
Masalahnya, hukum berjalan tertinggal dari kenyataan sosial. Regulasi telekomunikasi masih memperlakukan kuota sebagai layanan temporal, bukan sebagai nilai ekonomi yang telah berpindah tangan. Padahal, dalam logika transaksi, ketika konsumen membayar paket data, pada saat itu pula terjadi peralihan hak atas sejumlah volume data tertentu. Ia dibeli, bukan dititipkan.
Di sinilah ketimpangan bekerja. Relasi antara penyedia layanan dan konsumen berlangsung dalam kondisi asymmetry of power. Operator menetapkan aturan, konsumen menyetujui—tanpa ruang tawar yang nyata. Penghangusan kuota tampil sebagai kebijakan administratif yang sah, tetapi menyisakan persoalan etis dan konstitusional.

Karl Marx pernah menulis bahwa dalam kapitalisme, relasi produksi selalu melahirkan ilusi kesetaraan. Di permukaan, transaksi tampak adil: uang ditukar dengan komoditas. Namun di balik itu, terdapat relasi kuasa yang timpang, di mana pemilik modal mengendalikan syarat, waktu, dan batas penggunaan komoditas tersebut. Kuota internet adalah contoh mutakhir dari relasi ini.
Kuota dijual sebagai komoditas, tetapi kepemilikannya tidak pernah sepenuhnya berpindah. Konsumen membayar, namun nilai guna (use value) komoditas itu dibatasi oleh waktu yang ditentukan sepihak. Ketika masa aktif habis, nilai tukar (exchange value) telah diserap oleh sistem, sementara nilai guna yang tersisa dilenyapkan. Inilah bentuk penghisapan yang halus—bukan melalui pemotongan upah, tetapi melalui penghapusan nilai yang telah dibeli.
Ketika internet telah beralih dari sekadar fasilitas menjadi kebutuhan pokok, di situlah keberhasilan kapitalisme bekerja sebagaimana dibaca Marx: menguasai sarana-sarana kehidupan, lalu menormalisasi mekanisme penghisapan agar tampak wajar, legal, dan nyaris tak terasa.
Penghisapan ini tidak hadir dalam bentuk paksaan kasar. Ia datang sebagai “masa aktif”, “syarat dan ketentuan”, serta “kebijakan layanan”. Konsumen tidak merasa dirampas, karena kehilangan terjadi perlahan, terfragmentasi, dan dilembagakan. Marx menyebut kondisi ini sebagai fetisisme komoditas—ketika relasi sosial disamarkan menjadi hubungan antara benda dan aturan teknis.
Bandingkan dengan token listrik. Sisa daya tidak hangus meski tak langsung digunakan. Negara mengakui adanya nilai yang melekat pada satuan energi yang telah dibayar. Ketika logika serupa tidak diterapkan pada kuota internet, maka yang terjadi bukan sekadar perbedaan kebijakan sektoral, melainkan pembedaan perlindungan hukum terhadap jenis komoditas tertentu—yang kebetulan sangat menguntungkan industri digital.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebenarnya memberi landasan yang jelas. Pasal 4 dan Pasal 7 menegaskan hak konsumen atas manfaat yang sepadan dengan nilai transaksi serta kompensasi atas kerugian. Namun dalam praktik kuota internet, prinsip ini seolah dikesampingkan demi efisiensi pasar.
Gugatan ini, karenanya, bukan sekadar perkara kuota. Ia adalah kritik terhadap negara yang membiarkan logika akumulasi modal bekerja tanpa koreksi.
Dengan mengesahkan norma yang membuka ruang penghangusan kuota tanpa perlindungan nilai sisa, negara berisiko melakukan constitutional omission—membiarkan hak warga larut dalam mekanisme pasar.
Tuntutan pemohon pun tidak radikal: akumulasi sisa kuota, konversi ke pulsa, atau pengembalian dana secara proporsional. Sebuah permintaan sederhana agar nilai yang telah dibayar tidak lenyap begitu saja.
Mahkamah Konstitusi kini dihadapkan pada pilihan penting: terus memandang internet sebagai layanan tambahan, atau mengakuinya sebagai bagian dari kebutuhan dasar warga negara di era digital.
Sebab jika kuota yang dibayar boleh dihapus, maka seperti diingatkan Marx, persoalannya bukan lagi soal teknologi, melainkan tentang siapa yang berdaulat atas nilai—rakyat sebagai pembeli, atau sistem yang terus menagih tanpa pernah sepenuhnya memberi.
Dalam sistem seperti ini, yang diuji bukan lagi kualitas jaringan, melainkan batas kesabaran publik terhadap kehilangan yang terus dinormalisasi.
Ditulis oleh: Heriyosh
Editor: Redaksi Kopipahit.id