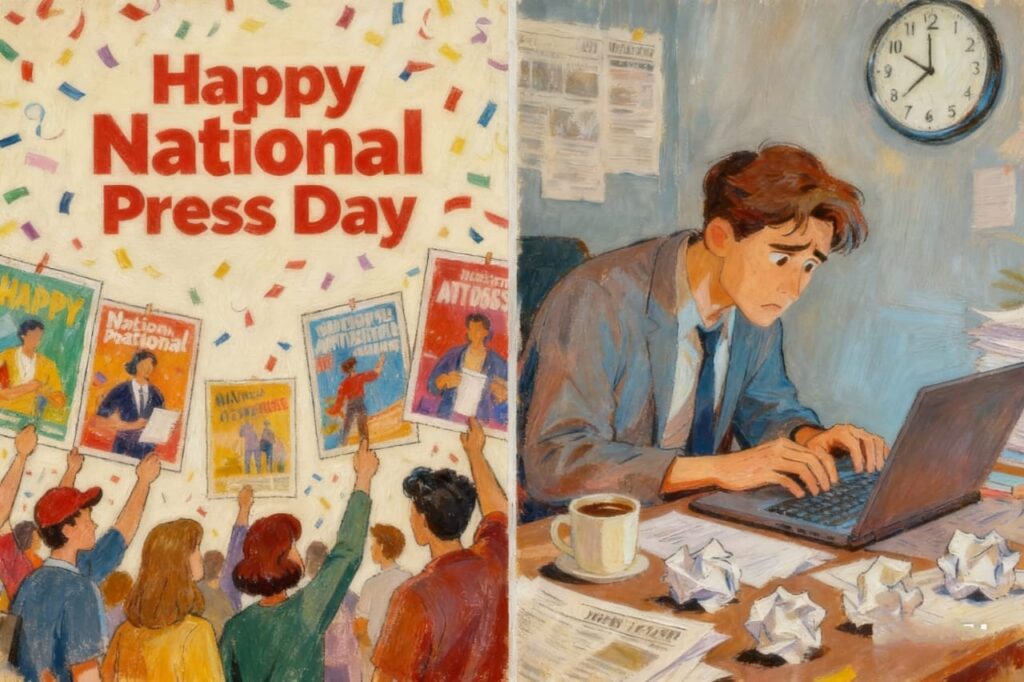Pada masa kolonial, perut rakyat Indonesia sering kali menjadi ruang eksperimen paling kejam. Eksploitasi ekonomi mengeringkan lumbung, memiskinkan keluarga, dan memaksa masyarakat mencari apa pun yang bisa direbus. Dari semua yang tersisa, bonggol pisang adalah salah satu yang paling jujur: ia tidak pernah mengklaim diri sebagai makanan lezat. Ia hanya bilang, “Aku bisa membuatmu tetap hidup besok pagi.”
Itu saja sudah cukup.
Namun justru dari titik itu kita melihat kecerdasan rakyat yang entah bagaimana selalu bisa lolos dari perangkap kelaparan. Bayangkan: bagian tanaman yang biasanya dianggap sampah, diolah menjadi sayur, tumis, bahkan campuran kue. Di masa ketika kolonialisme merampas sawah dan hasil panen, kreativitas di dapur menjadi bentuk perlawanan yang paling sunyi.
Ironis sekali bahwa yang kita sebut “makanan orang susah” itu ternyata kaya serat, vitamin, mineral, dan rendah gula. Tapi begitulah hidup: yang menyelamatkan biasanya tidak glamor. Yang mematikan sering hadir dalam bungkus modern dengan nama keren.
Sekarang, meja makan kita dipenuhi makanan instan, produk olahan, minuman manis yang diklaim “menyegarkan”—semuanya enak, cepat, dan pelan-pelan menggerogoti tubuh. Kita sibuk mengejar “lifestyle sehat”, tetapi jarang benar-benar memahami apa yang sehat itu sendiri. Kita membuang warisan pangan lokal, lalu membeli kembali versi mahalnya dalam bentuk “superfood” impor. Kalau bukan tragis, ini lucu.
Sementara itu, bonggol pisang diam saja. Tidak tersinggung, tidak menuntut pengakuan. Ia hanya tetap berada di sana, tumbuh di pekarangan, menunggu siapa tahu ada yang mau kembali belajar tentang ketahanan dari hal yang sederhana.
Kita sering lupa bahwa makanan bukan sekadar apa yang masuk ke tubuh, tetapi juga cerita tentang bagaimana sebuah bangsa bertahan melewati masa paling gelap. Makan bonggol pisang di masa kolonial bukan pilihan kuliner—itu pilihan hidup. Dan rakyat yang memakannya tidak sedang membangun tren, tetapi mempertahankan martabat.
Pada akhirnya, tradisi pangan seperti ini mengingatkan kita bahwa kecerdasan tidak selalu lahir dari ruang kelas. Terkadang ia tumbuh dari dapur reyot, dari tungku yang nyalanya kecil, dari ibu-ibu yang mengaduk bonggol pisang sambil berdoa agar besok tidak lebih buruk dari hari ini.
Zaman boleh berubah, tetapi pola pikir kadang tetap kolonial. Kita masih sering meninggikan makanan impor, merendahkan yang lokal, dan merasa modern hanya karena memegang sendok garpu stainless steel.
Di tengah dunia yang semakin cepat, sibuk, dan penuh bising, bonggol pisang hadir sebagai teguran halus yang agak nakal:
bahwa yang sering kita remehkan justru lebih pintar menjaga hidup kita daripada makanan yang kita banggakan di Instagram.
Dan barangkali, sebelum semuanya terlambat, kita perlu menengok kembali apa yang pernah menyelamatkan nenek moyang kita. Tidak untuk romantisasi kemiskinan, tetapi untuk mengingat bahwa kreativitas dan daya hidup tidak pernah datang dari kenyamanan.
Kadang dari bonggol pisang yang keras, basah, dan dipotong seadanya.
Kadang dari sejarah yang tidak pernah benar-benar kita cerna.
Ah, sudahlah. Mari kita nikmati kopi pahit lagi.
Editor: Jef KP