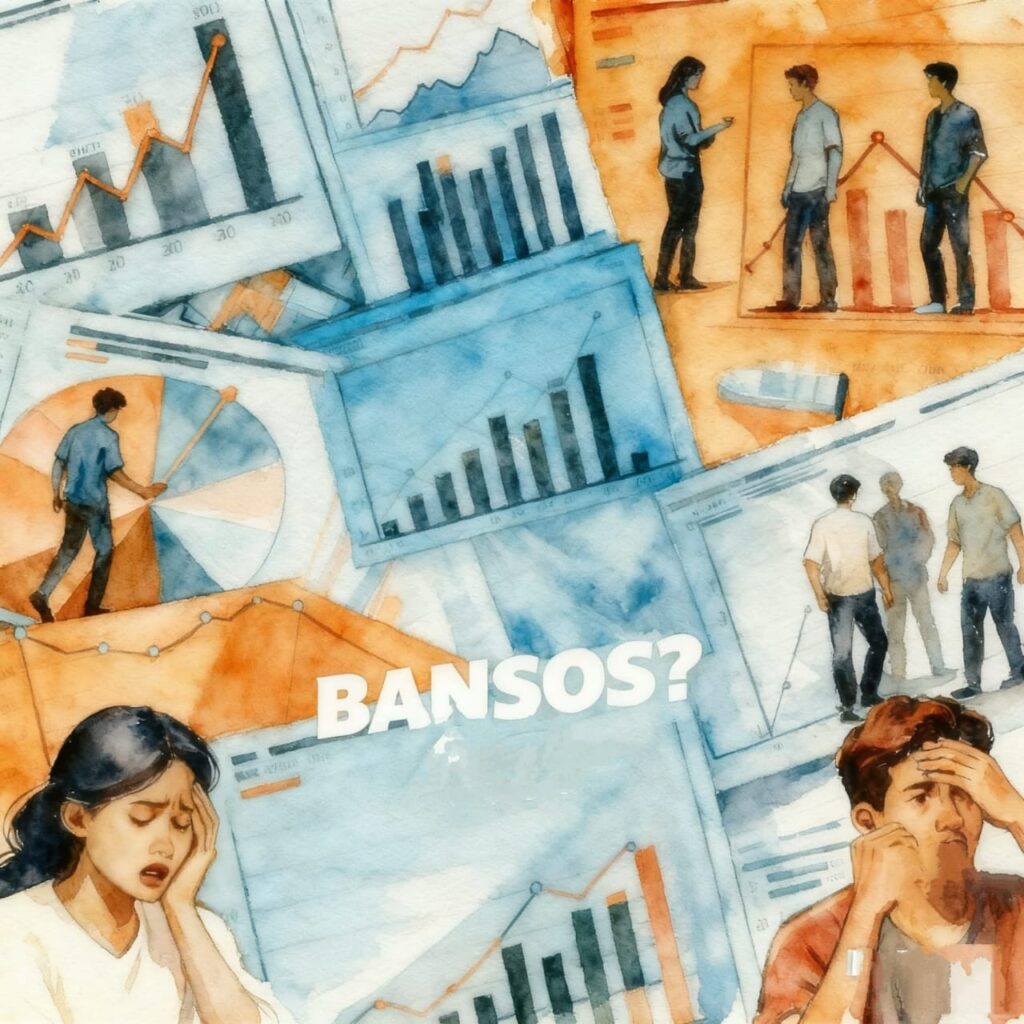LAMPUNG — Harga singkong di Lampung rasanya seperti sinetron yang entah kapan tamatnya. Pemerintah bikin aturan, pengusaha bikin akal-akalan, petani tetap jadi pemeran figuran yang kebanyakan adegan nangisnya.
Pergub Nomor 36 Tahun 2025 diluncurkan dengan wajah serius—seolah negara baru saja menemukan jurus rahasia menyelamatkan petani. Namun, yang terjadi justru mirip adegan komedi gelap: sehari sebelum aturan berlaku, sejumlah pabrik tapioka buru-baru pasang pengumuman, “Pabrik tutup sementara. Hanya bongkar yang sudah antre.”
Kalimat yang lebih mirip sindiran ketimbang pengumuman resmi.
Ada pula pabrik yang pura-pura patuh pada Pergub, tapi diam-diam memainkan jurus lama: timbangan ngaco.
“Satu mobil bisa hilang dua ton, Mas…” curhat seorang petani di media sosial.
Dua ton itu bukan angka. Itu harapan petani yang digerogoti pelan-pelan.
Pemerintah Lampung, dari DPRD hingga Gubernur, sudah berulang kali janji akan “membantu meningkatkan harga singkong.”
Masalahnya, yang meningkat tiap bulan justru angka kekecewaan petani, bukan harga singkongnya.
Pengusaha? Mereka memilih jalan yang lebih sederhana: beli singkong semurah mungkin, akali kadar pati, dan kalau bisa, “main mata” dengan timbangan. Efisien, tapi menyakitkan.
Seorang petani di Tulang Bawang Barat menumpahkan uneg-unegnya.
“Aturan banyak, tapi gak ada yang berani menindak pabrik. Kami makin terpuruk.”
Sementara itu, dari kubu pengusaha, jawabannya klise dan dingin:
“Harga rendah karena produksi berlebih. Pasar gak minta, jadi kami gak bisa beli mahal.”
Seolah semua persoalan selesai dijelaskan lewat satu kalimat.
Drama ini sebenarnya sudah tayang sejak tahun lalu. SKB, harga rekomendasi, refaksi, rapat koordinasi, foto bersama—semua sudah dicoba. Belum ada yang berhasil menyentuh akar persoalan.
Desember 2024, SKB menetapkan harga Rp1.400/kg. Hasilnya? Banyak pabrik menerapkan SKB ala mereka sendiri—dibumbui potongan dan kecurangan.
Lalu terbit Surat Edaran Gubernur Nomor 7 Tahun 2025. Belum sempat hangat, muncul lagi Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Harga penetapan sementara Rp1.350/kg dengan rafaksi maksimal 30 persen. Masalahnya: 30 persen itu maksimal atau minimal?
Di lapangan, potongan bisa terasa seperti 40 persen—kadang lebih, tergantung selera pabrik.
Kementerian Pertanian akhirnya turun tangan. Surat Dirjen Tanaman Pangan B-2218/TP.220/C/09/2025 menetapkan harga Rp1.350/kg, rafaksi maksimal 15 persen.
Aturannya cantik, rapatnya ramai, fotonya rapi. Tapi begitu sampai pabrik, aturan itu berubah menjadi sekadar dekorasi dinding.
Beberapa petani melapor:
“Masih ada yang bayar di bawah Rp1.000. Rafaksinya sadis.”
Lalu pada Hari Pahlawan, 10 November 2025, Pergub 36/2025 resmi berlaku. Hasilnya? Lagi-lagi plot twist. Banyak pabrik di Lampung Utara memilih tutup.
HAP sudah ditetapkan, tapi yang terjadi justru petani tidak punya tempat menjual singkong.
Petani kemudian limbung: mau tetap tanam singkong, harga tak jelas; mau pindah ke jagung, butuh modal baru. Sebagian akhirnya memilih tanam jagung—setidaknya pembelinya jelas, harganya lebih stabil, dan rafaksi tidak seperti potongan rambut ala pabrik yang sesukanya.
Akar masalahnya rumit, tapi sederhana kalau jujur: Kualitas singkong belum seragam. Biaya angkut dan produksi makin tinggi. Impor tepung tapioka lebih murah. Industri lebih memilih yang murah daripada yang dekat.
Sisanya adalah drama yang terus diputar ulang: aturan dibuat, pabrik menghindar, pemerintah menonton sambil sesekali bersuara, dan petani kembali bertanya; “Sebenarnya siapa yang kalian bela?”
Cerita ini belum tamat.
Dan seperti biasa, yang paling pahit tetap ditelan petani.
Ah, sudahlah. Mari kita nikmati kopi pahit lagi.
Reporter : J. Farhan
Editor : Redaksi Kopipahit.id