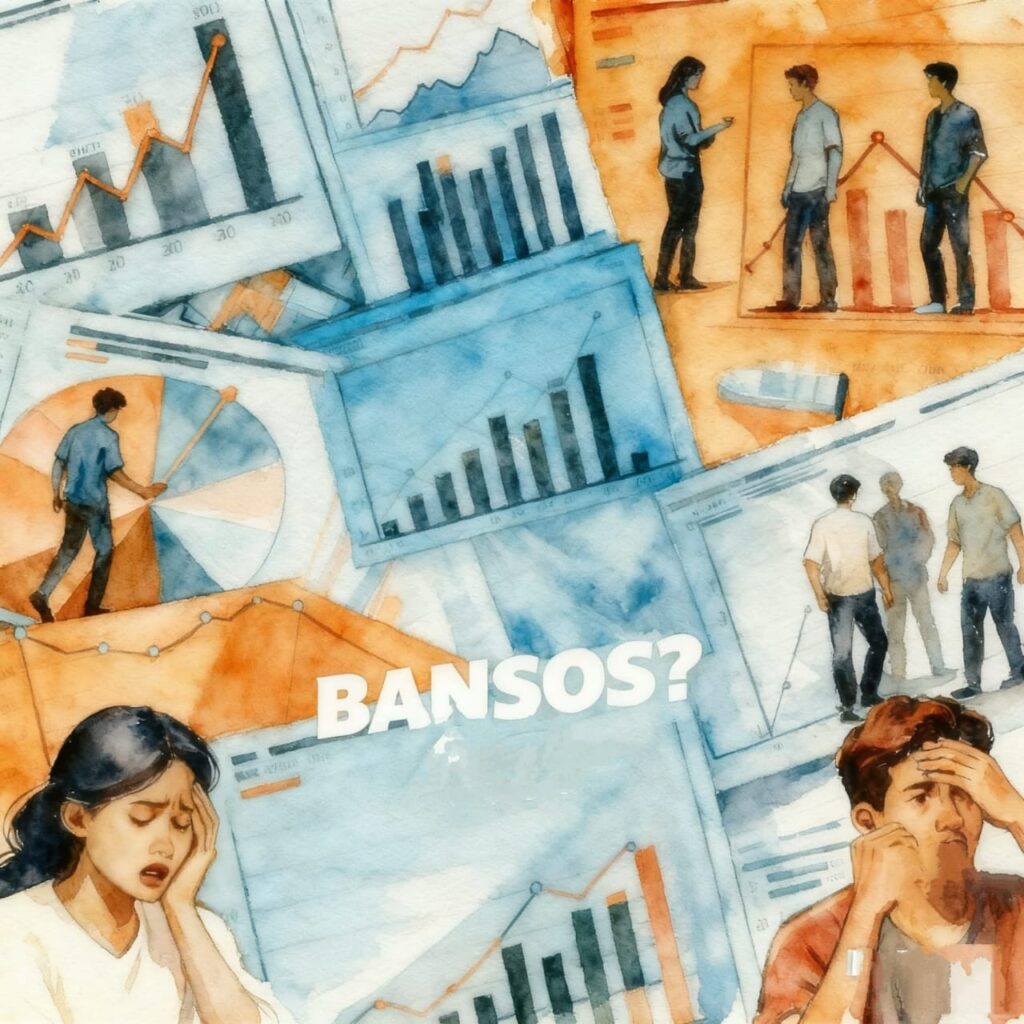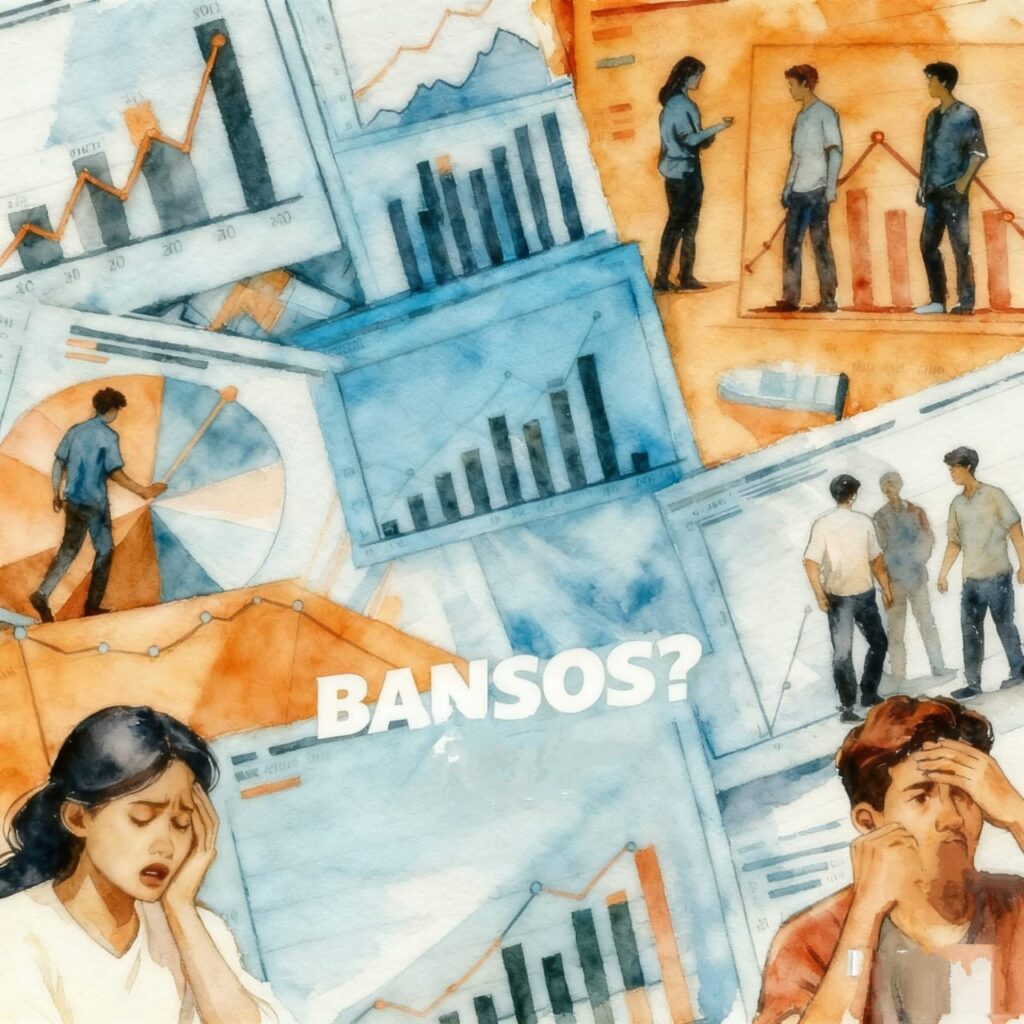
KOPIPAHIT.ID – Di Karanganyar, bantuan sosial kembali jadi sumber bisik-bisik panjang di warung, di pos ronda, sampai di balai dusun. Bukan karena bantuan itu tidak ada, tetapi karena ia datang dengan alamat yang keliru. Salah satu kasus mencuat dari Jaten. Seorang kepala dusun, yang memilih tak disebutkan namanya, menyebut banyak penerima BLT dan bantuan sosial lain yang secara kasat mata sudah tak lagi layak, tetapi tetap menerima. Sementara yang hidupnya kian terhimpit justru luput dari daftar.
Ini bukan cerita tunggal. Keluhan serupa berulang di wilayah lain. Polanya sama: data tak nyambung dengan realitas. Aparat di tingkat paling bawah tahu persis siapa warganya yang miskin, siapa yang sekadar pernah miskin, dan siapa yang hari ini justru hidup nyaman. Tapi pengetahuan itu mentok di meja birokrasi.
Jawaban yang diterima pun klise dan nyaris seragam: data dari pusat. Kalimat ini terdengar administratif, dingin, dan aman. Ia menjelaskan segalanya, sekaligus meniadakan tanggung jawab siapa pun di daerah. Desa hanya mengusulkan. Dinas hanya menyalurkan. Negara hadir sebagai kurir, bukan sebagai penilai keadilan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Sulistyowati, menjelaskan bahwa sejak April 2025 pemerintah menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebuah sistem yang menggabungkan DTKS, P3KE, dan Regsosek. Tujuannya mulia: satu data untuk semua. Tak boleh lagi ada OPD berjalan dengan data masing-masing.
Masalahnya, satu data tidak otomatis berarti data yang benar.
DTSEN datang membawa janji keteraturan, tetapi juga mewarisi kekacauan lama. Ketidaktepatan sasaran yang terjadi hari ini, menurut Dinsos, masih banyak bersumber dari data sebelum DTSEN diberlakukan. Artinya, yang kita saksikan sekarang adalah masa transisi—masa di mana warga menanggung ongkos kesalahan sistem.
Pendataan lapangan dilakukan oleh petugas yang dikoordinasikan BPS. Desa, lewat petugas PMK, hanya bertugas menginput usulan. Dinsos berada di tengah: berkoordinasi, memverifikasi, dan menunggu. Semua bergerak sesuai prosedur. Tapi prosedur sering kali bergerak lebih lambat dari perubahan hidup warga.
Untuk meredam kritik, pemerintah membuka kanal partisipasi. Warga dipersilakan menyanggah. Memotret rumah tetangganya yang sudah layak. Mengunggah bukti bahwa seseorang tak lagi miskin. Setiap tiga bulan, data diperbarui. Secara teori, sistem ini tampak demokratis.
Namun di lapangan, beban koreksi justru dilempar ke warga. Negara hadir sebagai administrator aplikasi, sementara masyarakat diminta menjadi pengawas, pelapor, sekaligus saksi. Ketika terjadi kecemburuan sosial, konflik horizontal pun mengintai. Yang dipertanyakan warga bukan sekadar bantuan, melainkan keadilan.
Ironisnya, kelompok desil 1 sampai 4 tetap menerima bantuan meskipun data belum sepenuhnya tervalidasi. Alasannya sederhana: mereka dianggap paling rentan. Tapi di sinilah masalah itu berlapis. Ketika data lama tak segera dibersihkan, mereka yang sudah naik kelas secara ekonomi tetap aman di daftar penerima, sementara yang baru jatuh miskin harus menunggu siklus pembaruan berikutnya.
Bantuan sosial akhirnya menjadi semacam lotre administratif. Siapa yang tertangkap sistem, dia yang selamat. Bukan siapa yang paling membutuhkan.
Polemik bansos di Karanganyar memperlihatkan satu soal mendasar: negara masih lebih percaya pada data daripada pada warganya sendiri. Padahal, kemiskinan bukan sekadar angka desil. Ia adalah cerita yang berubah cepat—hari ini bekerja, besok bangkrut; hari ini sehat, besok sakit.
Selama koreksi data lebih patuh pada jadwal sistem ketimbang pada kenyataan sosial, selama perangkat desa hanya diposisikan sebagai penginput bukan pengambil keputusan, maka kisah salah sasaran ini akan terus berulang.
Dan di setiap tiga bulan pembaruan data itu, selalu ada warga yang keburu lapar sebelum namanya sempat masuk daftar.
Jika Pemerintah Daerah benar-benar ingin keluar dari lingkaran salah sasaran bantuan sosial, maka yang perlu dibenahi bukan sekadar aplikasinya, melainkan cara pandang terhadap kemiskinan itu sendiri.
Pertama, beri kewenangan korektif yang nyata kepada desa. Bukan sekadar hak mengusulkan atau menginput, tetapi kewenangan terbatas untuk membekukan sementara penerima yang secara kasat mata sudah tidak layak, sambil menunggu verifikasi berikutnya. Desa bukan mesin ketik data, melainkan unit sosial yang hidup bersama warganya.
Kedua, hentikan mitos bahwa data pusat selalu lebih benar daripada pengetahuan lokal. DTSEN boleh menjadi acuan nasional, tetapi pemerintah daerah semestinya berani mencatat dan melaporkan anomali secara terbuka dan berkala. Transparansi ini penting agar kesalahan sistem tidak terus diwariskan dari satu periode ke periode berikutnya.
Ketiga, jangan lemparkan beban koreksi sepenuhnya ke masyarakat. Mekanisme sanggah memang perlu, tetapi ia tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menghindari tanggung jawab negara. Tidak semua warga berani melapor. Tidak semua konflik bisa diselesaikan lewat unggah foto rumah tetangga.
Keempat, percepat siklus pemutakhiran untuk kasus ekstrem. Warga yang jatuh miskin karena sakit, PHK, atau bencana tidak bisa disuruh menunggu tiga bulan demi belas kasihan sistem. Pemerintah daerah harus memiliki skema respons cepat berbasis rekomendasi desa.
Terakhir, pemerintah daerah perlu berani mengatakan satu hal yang selama ini dihindari: bantuan sosial bukan sekadar soal kuota dan desil, tetapi soal keadilan. Selama kebijakan sosial lebih tunduk pada prosedur ketimbang pada kenyataan hidup warga, maka setiap polemik bansos hanyalah jeda sebelum kegaduhan berikutnya.
Dan jika negara ingin kembali dipercaya, maka ia harus mulai belajar satu hal sederhana: mendengarkan warganya, bukan hanya datanya.
Ditulis oleh: Heriyosh
Editor: Redaksi Kopipahit.id