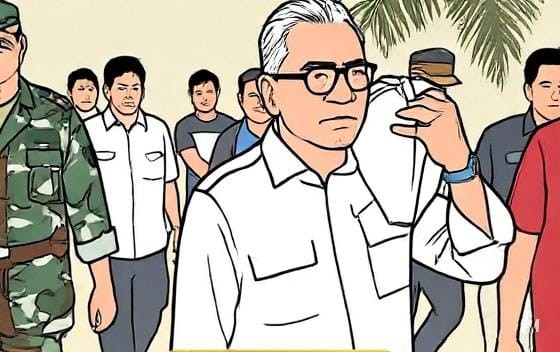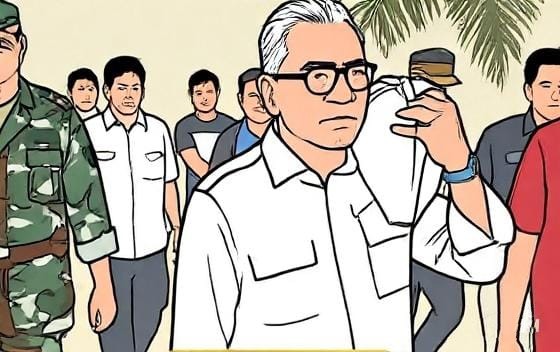
KOPIPAHIT.ID – Duka di Sumatera kembali membuka tabir lama: setiap kali bencana datang, pejabat datang bergantian. Mereka turun dari mobil mewah, mengulurkan tangan pada warga yang kehilangan rumah, mengangkat sekop, membersihkan lumpur, atau memanggul satu karung beras. Semua dilakukan dalam hitungan detik—cukup untuk ditangkap kamera, cukup untuk menjadi materi unggahan, cukup untuk membangun citra.
Pertanyaannya sederhana: apakah hidup mereka sehari-hari memang seperti itu? Apakah ketika bencana kecil menimpa rakyat di pelosok, mereka juga hadir? Apakah saat kedukaan terjadi, mereka juga datang tanpa kamera, tanpa protokol, tanpa skenario? Pertanyaan ini mencuat bukan karena kita sinis, tapi karena publik sudah terlalu sering disuguhi pola yang sama.
Kita sering lupa bahwa apa yang terjadi hari ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah bayangan panjang dari kebijakan yang diambil bertahun-tahun lalu. Mereka yang pernah mengobral izin pembalakan, membuka hutan tanpa kendali, atau menandatangani dokumen yang mengorbankan ruang hidup rakyat, kini berdiri di antara puing, lumpur, dan kayu-kayu besar yang hanyut ke pemukiman. Ironisnya, yang mereka hadapi adalah konsekuensi dari tangan mereka sendiri.
Kita masih ingat percakapan seorang menteri kehutanan dengan Harrison Ford—ketika sang aktor menegur langsung kebijakan pembukaan hutan. Kala itu, publik tersentak. Bukan hanya karena teguran itu terekam, tapi karena ia membongkar apa yang selama ini ditutupi. Pesannya jelas: dalam setiap krisis, kebenaran akan muncul ke permukaan.
Hari ini, kita kembali menyaksikan itu. Pesawat-pesawat para pejabat mendarat bergantian di Medan, Silangit, Nias, Aceh, hingga Padang. Mereka berebut hadir lebih cepat, berebut menunjukkan empati lebih dulu. Namun publik—yang semakin cerdas, semakin peka—bertanya dalam hati: apa yang sebenarnya sedang dilakukan? Empati, atau eksibisi?
Kayu-kayu gelondongan yang menghantam rumah warga bukan datang begitu saja. Mereka adalah saksi bisu dari puluhan tahun deforestasi yang dilegalkan. Mereka turun mengikuti arus banjir seperti membawa pesan: “Inilah hasil dari apa yang kalian biarkan.” Alam tidak pernah berbohong, dan hari ini ia bersuara lebih keras daripada pejabat manapun.
Di tengah duka itu, generasi muda melihat sesuatu yang lain. JS. Khairen, seorang penulis buku “Dompet Ayah Sepatu Ibu”, menggambarkan Sumatera dengan teks yang menusuk:
“Kekayaan Sumatera adalah kekayaan nasional. Tetapi mengapa bencananya bukan bencana nasional?”
Pertanyaan itu menggema di kepala banyak anak muda hari ini. Ada ironi besar di sana: sumber daya alam Sumatera diekstraksi untuk kepentingan nasional, tetapi ketika bencana menerjang, rasa tanggung jawab itu seperti menguap di udara.
Alam adalah pinjaman. Bukan dari leluhur, tapi dari anak-anak kita, dari generasi yang belum lahir. Namun bagaimana mungkin kita mengembalikan pinjaman itu dalam keadaan utuh jika para pengambil kebijakan bersikeras menutup jejak mereka dengan sekarung beras dan beberapa detik aksi di depan kamera?
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah pejabat mampu menutupi kesalahan mereka. Pertanyaannya adalah: berapa lama lagi publik akan bersabar melihat sandiwara yang sama berulang-ulang?
Dan seperti biasa, rakyat tidak meminta banyak—hanya satu hal:
kerjakan tugasmu dengan benar, tanpa pencitraan, tanpa menipu alam, tanpa merampas masa depan generasi berikutnya.
Di sinilah letak persoalan kita:
apakah para pejabat siap memilih kejujuran yang pahit, atau terus menyesap manisnya pencitraan — hingga bencana berikutnya berbicara lebih keras dari hari ini?
Ditulis oleh: Heriyosh
Editor: Redaksi Kopipahit.id