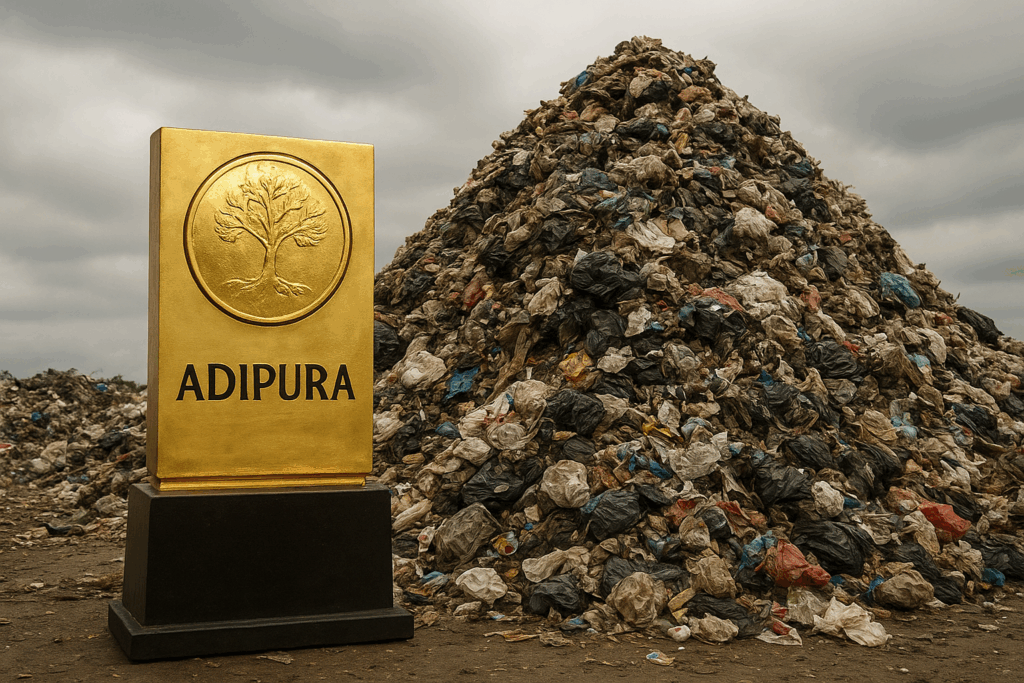Kalau ada satu ruangan yang paling tenang di negeri ini, mungkin itu “Ruang Pahlawan.”
Putih, bersih, dan berbau bunga kenanga. Wajah-wajah besar tergantung rapi di dinding — senyum tegas, jas rapi, mata yang menatap entah ke masa depan atau ke masa lalu. Semua tampak heroik, meski sebagian dari mereka, kalau boleh jujur, mungkin juga bagian dari masalah yang bikin rakyat menderita.
Lalu di antara deretan wajah gagah itu, berdirilah satu sosok yang tidak pernah pakai pangkat atau seragam.
Marsinah.
Blusnya pudar, celananya lusuh, sepatunya sepatu karet pabrik. Medali emas menggantung di dadanya bertuliskan: “Pahlawan Nasional Republik Indonesia.” Kalau ada petugas museum yang kurang teliti, mungkin dia bakal salah paham, “Maaf, Mbak, ini ruang pahlawan, bukan ruang tamu buruh.”
Tapi justru di situlah lucunya sejarah kita. Dulu Marsinah diculik karena bersuara membela kaum buruh. Sekarang, dia dihormati karena diam.
Kalimat itu mungkin terdengar pahit, tapi begitulah cara bangsa ini mencintai para pemberani: telat, dan biasanya baru setelah mereka mati. Kalau bisa ngomong, mungkin Marsinah bakal bilang, “Wah, penghargaan ini datangnya 30 tahun terlambat, tapi ya sudahlah. Namanya juga negara, suka repot sendiri kalau soal kebenaran.”
Marsinah tidak lahir dari panggung politik. Ia bukan ketua serikat besar, bukan aktivis yang sering diwawancarai media. Ia hanya buruh perempuan di Pabrik jam tangan, Jawa Timur, yang berani protes soal upah.
Tahun 1993, ia hilang setelah memimpin aksi. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di sebuah gubuk di Nganjuk. Ada luka-luka yang tak perlu dijelaskan ulang di sini — terlalu kejam untuk diingat, terlalu penting untuk dilupakan.
Kasusnya diusut, tentu saja. Tapi seperti biasa, pengusutan di negeri ini sering berakhir dengan kalimat ajaib: “belum cukup bukti.”
Dan sejak saat itu, nama Marsinah melayang-layang di udara, jadi legenda. Kadang disebut di spanduk demonstrasi, kadang di mural, kadang di naskah teater kampus. Tapi jarang disebut di rapat kabinet.
Bangsa ini memang suka sekali mengubah tragedi jadi dekorasi.
Keadilan belum datang, tapi sudah ada piagam, bunga, dan upacara.
Bayangkan, kalau Marsinah benar-benar diundang ke Ruang Pahlawan itu. Di sana, duduk seorang lelaki tua berjas abu-abu, dengan wajah dingin dan senyumnya yang khas di bawah peci hitam — mungkin salah satu tokoh penting masa lalu — dengan medali yang sama di dadanya. Ia tersenyum sopan, lalu berkata, “Begitulah sejarah, Nak. Yang dulu dianggap pengganggu, sekarang disanjung.”
Marsinah mungkin akan menjawab pelan, “Menarik juga dengar itu dari orang yang dulu punya kekuasaan atas segalanya.”
Nadanya tenang, tapi jujur. Tidak marah, hanya getir.
Si lelaki mungkin akan membalas, “Kami hanya menjaga stabilitas waktu itu.”
Ah, kata “stabilitas.”
Kata yang terdengar manis, padahal sering jadi alasan untuk menindas. Marsinah tahu betul, stabilitas waktu itu dibayar dengan suara yang dibungkam, termasuk suaranya sendiri.
Kalau percakapan itu benar terjadi, ruangan itu mungkin mendadak hening. Sebab di antara mereka, udara akan terasa tebal — bukan karena marah, tapi karena kesadaran yang datang terlambat.
Seorang perempuan berkerudung di dekat pintu mungkin akan mencoba menengahi, “Sudahlah, Marsinah. Sekarang namamu sudah dihormati. Itu tanda bangsa ini menyesal.”
Marsinah bisa saja tersenyum kecil, lalu berkata, “Penghormatan tanpa keadilan itu seperti nisan tanpa kubur. Cantik, tapi kosong.”
Dan kita yang mendengar mungkin akan diam. Karena kalimat itu menampar pelan tapi dalam.
Memang begitulah cara bangsa ini berdamai dengan masa lalunya: dengan simbol, bukan keberanian. Dengan gelar, bukan kebenaran.
Selalu ada rasa bersalah yang disembunyikan di balik upacara dan pidato.
Padahal kalau dipikir-pikir, Marsinah tidak pernah meminta dihormati. Ia hanya menuntut yang sederhana: hak sebagai pekerja, upah yang adil, dan kebebasan untuk bersuara. Tapi negara waktu itu memilih menutup telinga. Sekarang, setelah ia tiada, telinga itu baru dibuka lebar-lebar, hanya untuk mendengarkan lagu wajib di peringatan Hari Buruh.
Ironi macam apa itu?
Tiga puluh tahun berlalu, tapi tuntutan yang sama masih terdengar di jalan-jalan setiap 1 Mei.
Upah layak, jaminan kerja, hak berserikat. Seolah waktu tak bergerak.
Yang berbeda hanya spanduk dan format surat izin aksi.
Mungkin kalau Marsinah bisa lihat dari ruang sana, ia akan menghela napas panjang. “Kalian masih menuntut hal yang sama? Waduh, ternyata aku mati sia-sia, ya?”
Tapi tidak, Marsinah. Tidak sia-sia.
Namamu masih jadi alasan banyak orang berani melawan.
Meski negara belum menegakkan keadilan, keberanianmu sudah menyalakan nyala kecil di banyak dada — dan itu tidak bisa dimatikan.
Dan kini, sejak 10 November 2025, nama itu resmi diabadikan oleh negara.
Marsinah, buruh perempuan dari Sidoarjo, diangkat menjadi Pahlawan Nasional Republik Indonesia.
Sebuah keputusan yang akhirnya datang, meski mungkin agak telat tiga dekade.
Kalau bisa bicara, Marsinah barangkali hanya tersenyum kecil dan berkata, “Terima kasih. Tapi tolong, jangan cuma berhenti di medali. Karena medali tanpa keadilan itu cuma logam yang disepuh rasa bersalah.”
Sebab penghormatan sejati bukan di upacara, tapi di kebijakan yang berpihak.
Bukan di pidato pejabat, tapi di tangan buruh yang digenggam dengan hormat.
Keadilan yang tidak datang tepat waktu rasanya mirip kopi dingin: tetap pahit, tapi sudah kehilangan hangatnya.
Saya menyeruput kopi di pojok ruang imajiner itu, melihat Marsinah berjalan ke luar, menatap dinding tempat wajah-wajah besar menggantung diam.
Sebelum pergi, ia mungkin akan berkata pelan, “Terima kasih atas gelarnya. Tapi izinkan aku menunggu keadilan dulu, sebelum benar-benar merasa jadi pahlawan.”
Dan di belakangnya, potret-potret di dinding hanya bisa menatap bisu.
Angin sore masuk dari jendela, membawa aroma kenanga dan sedikit rasa bersalah.
Kopi saya sudah hampir habis. Tapi entah kenapa, rasanya malah makin pahit. (Ysp)